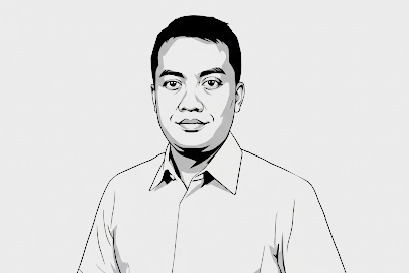
Oleh: Choirul Anam*
blokBojonegoro.com - Pak Darto menatap atap rumahnya yang terbuat dari seng yang mulai berkarat. Matahari menyengat, dan panas seolah menembus seluruh ruang. Di benaknya teringat pidato Presiden Prabowo Subianto beberapa minggu lalu, di mana ia mengenalkan sebuah gagasan baru bernama gentengisasi. Sebuah istilah yang bagi sebagian orang mungkin terdengar sederhana — mengganti atap seng dengan atap genteng — namun bagi banyak warga, gagasan itu sedang mengundang perdebatan dan renungan lebih dalam tentang bagaimana negara mempertimbangkan kesejahteraan rakyatnya.
Dalam forum Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah pada awal Februari 2026, Prabowo memperkenalkan gentengisasi sebagai bagian dari Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah). Ia ingin wajah permukiman Indonesia lebih berseri, lebih “indah” secara visual, serta memberi kenyamanan yang lebih baik bagi penghuni rumah. Seng, menurutnya, dianggap panas, mudah berkarat, dan kurang mencerminkan estetika Indonesia yang semestinya. Ia mengusulkan agar penggunaan genteng tanah liat menjadi standar, dengan keterlibatan Koperasi Merah Putih dan produksi lokal yang merakyat sebagai ujung tombak pelaksanaannya.
Kalau dilihat dari sisi estetika, narasi itu memiliki daya tarik — siapa yang tidak ingin tinggal di lingkungan yang tampak rapi dan nyaman? Namun di balik itu muncul sejumlah pertanyaan penting yang tidak boleh diabaikan begitu saja.
Pertama, realitas ekonomi rakyat yang beragam. Bagi warga seperti Pak Darto, penggantian atap bukan sekadar soal estetika. Itu soal anggaran yang tak sedikit. Bahan bangunan genteng yang tampak solid itu memerlukan biaya lebih besar dibandingkan seng murah yang selama ini dipilih warga karena keterbatasan dana. Seperti ditunjukkan oleh pengusaha bahan bangunan sendiri, genteng bisa mendatangkan peluang ekonomi lokal, tetapi pergeseran material konstruksi secara nasional tidak bisa disamaratakan tanpa melihat dampak sosial dan pembiayaan yang realistis bagi rumah tangga berpenghasilan rendah.
Kedua, dari sisi prioritas kebijakan publik, pertanyaan yang muncul adalah: apakah proyek estetika seperti gentengisasi menjadi urgensi negara sementara kebutuhan dasar lain — kesehatan, pendidikan, dan keamanan sosial — masih diperdebatkan dalam kehidupan sehari-hari warga?
Menyusul gagasan estetika bangunan itu, muncul gelombang kritik yang lebih serius terkait kebijakan kesehatan yang menyentuh kehidupan paling mendasar warga. Pada awal Februari 2026, sekitar 11 juta peserta program jaminan kesehatan nasional bersubsidi (PBI-JK) dinonaktifkan dari kepesertaannya. Penonaktifan ini terjadi karena data penerima bantuan dianggap tidak lagi memenuhi kriteria berdasarkan sistem Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang baru diterapkan pemerintah.
Berita ini menggerakkan keresahan luas. Data menunjukkan bahwa pencabutan tersebut memengaruhi layanan kesehatan penting, termasuk perawatan pasien gagal ginjal, yang kehilangan akses terhadap perawatan rutin seperti cuci darah tanpa pemberitahuan yang layak. Kritik pedas terhadap sistem ini datang dari tokoh masyarakat, seperti anggota DPD Fahira Idris, yang menekankan bahwa proses pemutakhiran data boleh jadi diperlukan untuk mengefisienkan program sosial, tetapi penerapannya harus menghormati hak dasar dan keselamatan pasien. Dalam beberapa kasus, warga baru menyadari status PBI mereka nonaktif ketika sudah berada di fasilitas kesehatan — momen yang sangat rentan dan berisiko.
Direktur BPJS Kesehatan bahkan menegaskan bahwa keputusan pencabutan semata merupakan implementasi data baru, bukan pengurangan jumlah total kepesertaan, karena peserta yang dihapus dianggap telah digantikan oleh orang lain yang lebih berhak. Namun realitasnya di lapangan tidak sesederhana itu. Warga yang bergantung pada subsidi kesehatan mendapati diri mereka terlempar tanpa jaminan pada saat yang paling membutuhkan.
Mensos Saifullah Yusuf, yang menjadi ujung tombak keputusan administratif ini, memandang penonaktifan berdasarkan pemutakhiran data sebagai langkah untuk “mendapatkan tepat sasaran” bantuan sosial. Meski demikian, kritik yang muncul dari komunitas medis dan legislatif menyoroti perlunya jangka waktu pemberitahuan yang memadai, serta mekanisme yang menjamin akses kesehatan tidak terganggu oleh perubahan administratif semata.
Kisah gentengisasi dan pencabutan jaminan kesehatan ini — meskipun berbeda dalam bentuk dan konteks — sejatinya menyentuh satu benang merah: bagaimana negara memutuskan prioritas kebijakan dan implikasinya terhadap kehidupan warga. Gentengisasi sekilas adalah sebuah simbol — simbol estetika, simbol kepedulian terhadap lingkungan, mungkin juga simbol kebangkitan ekonomi lokal melalui koperasi desa. Namun ketika simbol itu berdampingan dengan realitas pencabutan layanan kesehatan bagi jutaan warga paling rentan, kita tidak bisa hanya terpikat oleh simbol itu sendiri.
Kebijakan publik yang baik bukan hanya tentang visi besar dan jargon — seindah kata Indonesia ASRI — tetapi tentang bagaimana prioritas itu diterjemahkan ke dalam dampak nyata, terutama bagi mereka yang paling bergantung pada perlindungan negara: warga miskin, lansia, dan pasien dengan kebutuhan medis kronis. Estetika hunian yang indah memang penting, tetapi kehidupan yang sehat dan hak atas layanan kesehatan adalah landasan keberadaban sebuah negara. Ketika dua hal ini saling berbenturan secara naratif, kita ditantang untuk merenungkan kembali: kebijakan seperti apa yang benar-benar menyejahterakan rakyat Indonesia? Ini bukan sekadar soal genteng di atas rumah, tetapi tentang siapa yang berada di bawahnya — dan apakah mereka benar-benar dilindungi. [mu]
*Ketua PAC Ansor Balen



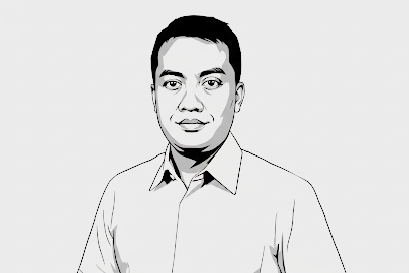
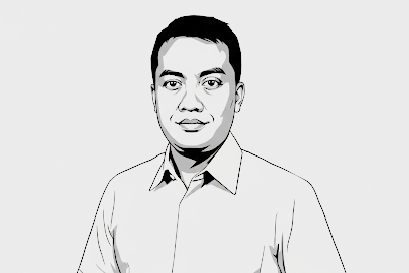












0 Comments
LEAVE A REPLY
Your email address will not be published